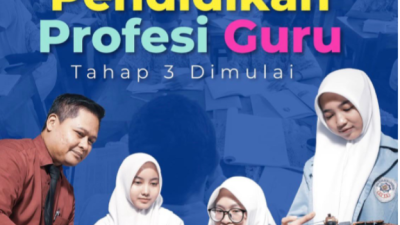Masalah perbatasan antara Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (Indonesia) dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) hingga kini masih menyisakan persoalan klasik: klaim dan kontra-klaim wilayah. Konflik ini kerap melibatkan masyarakat lokal yang tinggal di perbatasan, memunculkan gesekan sosial, bahkan potensi instabilitas keamanan.
Dalam perspektif hukum internasional, penyelesaian persoalan batas negara idealnya mengacu pada instrumen hukum yang diakui dunia. Namun, penting ditegaskan bahwa hukum internasional pada hakikatnya lebih bersifat seruan moral daripada hukum yang memiliki daya paksa layaknya hukum nasional. Akibatnya, implementasinya sering kali tidak efektif dan justru menimbulkan masalah baru.
Oleh karena itu, penyelesaian masalah perbatasan TTU–RDTL sebaiknya tidak hanya mengandalkan doktrin umum hukum internasional, melainkan mengembangkan pendekatan yang lebih kontekstual, yaitu melalui treaty contract.
Treaty Contract sebagai Solusi Kasus per Kasus
Konsep treaty contract, sebagaimana dikemukakan oleh ahli hukum internasional J.G. Starke dan Bernard Shaw, menekankan pentingnya penyelesaian perbatasan melalui perjanjian insidentil dan kasus per kasus berdasarkan kesepakatan dua negara. Pendekatan ini lebih realistis karena setiap persoalan perbatasan memiliki karakteristik berbeda—baik dari segi sejarah, sosial budaya, maupun geografis.
Dengan treaty contract, Indonesia dan Timor Leste dapat menyusun kesepakatan bilateral yang bersifat khusus, fleksibel, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat perbatasan.
Peran Proaktif Pemerintah Daerah dan Kearifan Lokal
Penyelesaian masalah perbatasan tidak bisa hanya dilakukan di tingkat pusat. Pemerintah daerah, khususnya TTU, perlu proaktif menjembatani komunikasi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Timor Leste.
Pendekatan berbasis kearifan lokal sangat penting dalam proses ini. Kearifan yang telah diwariskan turun-temurun oleh masyarakat adat di wilayah perbatasan dapat dikristalisasi ke dalam konsep transitional justice of law. Prinsip ini menekankan rekonsiliasi, keadilan transisional, serta kesepahaman yang lahir dari pengalaman hidup bersama di wilayah perbatasan.
Dengan demikian, hasil kesepakatan tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga berakar pada nilai budaya lokal yang diakui masyarakat kedua negara.
Regim Pengelolaan Perbatasan yang Jelas
Selain itu, dalam konteks menjaga kedaulatan dan hak berdaulat, diperlukan kepastian mengenai rezim hukum perbatasan yang digunakan. Apakah menggunakan soft regime (fleksibel, berbasis kerja sama sosial-budaya dan ekonomi) atau hard regime (tegas, berbasis delimitasi garis batas yang ketat).
Sebagai perbandingan, penyelesaian perbatasan antara Amerika Serikat dan Kanada telah berhasil mengkombinasikan pendekatan hard regime pada aspek keamanan dan soft regime pada aspek sosial-ekonomi. Model ini dapat menjadi rujukan dalam penanganan perbatasan Indonesia, baik dengan Timor Leste, Australia, Papua Nugini, maupun Filipina.
Penegasan Pemerintah Indonesia
Akhirnya, pemerintah pusat Indonesia perlu memberikan penegasan mengenai rezim perbatasan yang akan diterapkan. Tanpa kepastian, masyarakat di wilayah perbatasan akan terus hidup dalam ketidakjelasan, dan konflik akan terus berulang.
Penyelesaian masalah perbatasan TTU–RDTL bukan sekadar soal garis di peta, tetapi juga menyangkut kehidupan masyarakat lokal, hubungan antarnegara, serta citra Indonesia di mata internasional. Pendekatan treaty contract, kearifan lokal, dan rezim yang jelas menjadi kunci bagi penyelesaian yang adil, damai, dan berkelanjutan. **